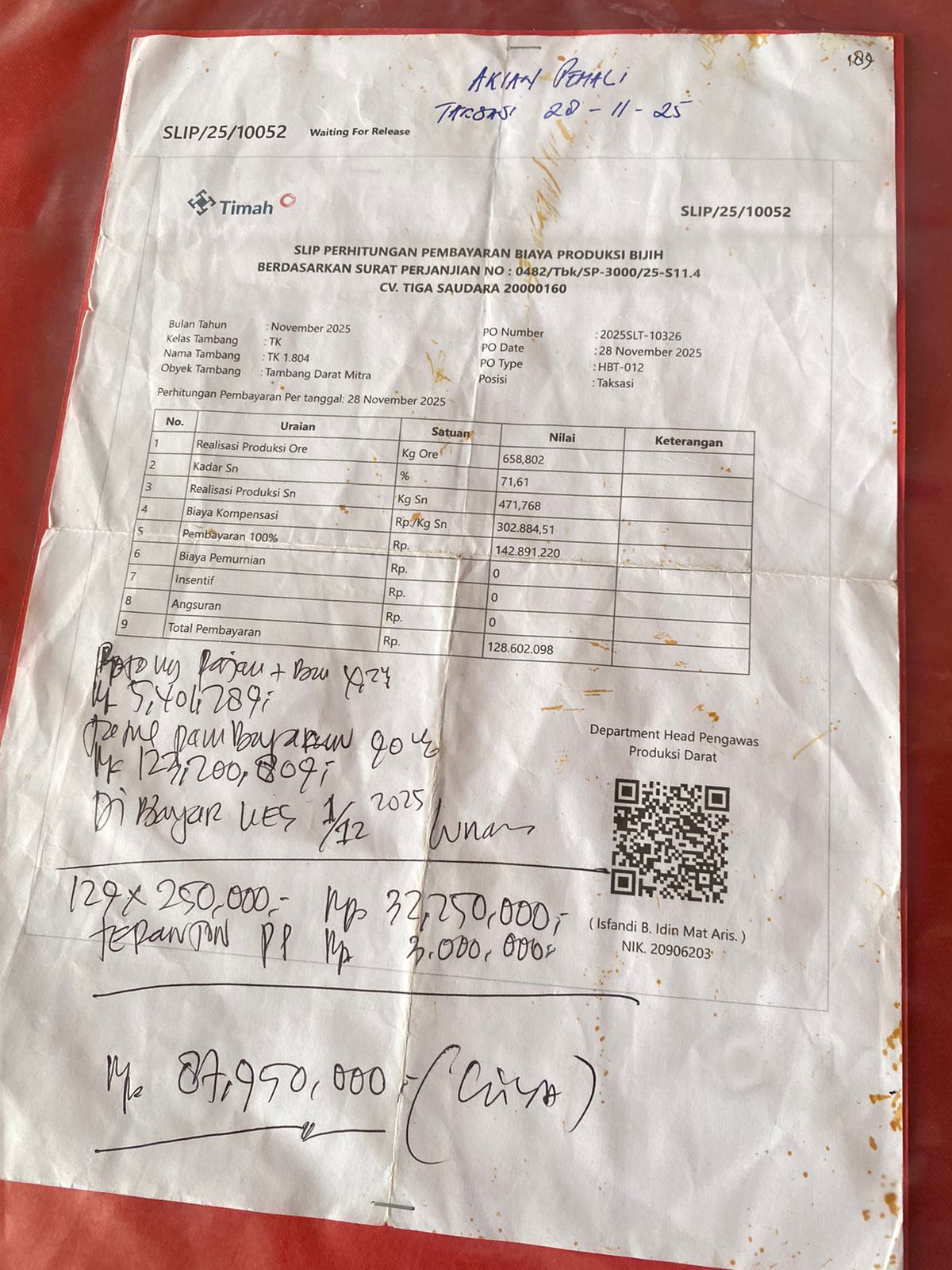Ideologisasi Islam: Membentuk Generasi Pelopor Perubahan di Tengah Hegemoni Digital

Penulis: Maryani, S.Pd (Pendidik dan Aktivis Dakwah Kampus)
Generasi muda hari ini hidup dalam genggaman layar. Sejak bangun tidur hingga larut malam, smartphone menjadi teman paling setia. Laporan Try Timeout, kelompok usia 18–24 tahun—yang didominasi Gen Z—dapat menghabiskan hingga sekitar 7,3 jam per hari di smartphone. Bahkan menurut laporan survei Alvara Research Center, pecandu internet atau addicted user paling banyak berasal dari kalangan generasi Z.
Saat ini, platform digital bukan lagi sekadar sarana hiburan, tetapi ruang utama pembentukan cara berpikir, nilai hidup, bahkan orientasi perjuangan generasi muda. Sebagai pelopor perubahan, generasi muda memang tidak pernah kehabisan ide kreatif. Aktivisme pemuda menemukan bentuk baru melalui media sosial. Meme, video pendek, tagar, petisi daring, hingga stand-up comedy mampu menggerakkan solidaritas massal. Tidak sedikit gerakan digital yang berlanjut menjadi aksi nyata di jalanan. Fenomena ini terlihat dalam berbagai protes mahasiswa dan gerakan pemuda, baik di dalam maupun luar negeri.
Namun, di sisi lain, ruang digital juga menyimpan bahaya laten. Platform digital secara perlahan membentuk identitas generasi muda dalam kerangka sekuler. Gaya hidup konsumtif, individualistik, dan relativisme moral diproduksi masif. Bersamaan dengan itu, berbagai persoalan muncul: jeratan pinjaman online, judi daring, perundungan digital, kekerasan seksual, hingga krisis kesehatan mental. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyoroti data yang menunjukkan rata-rata screen time orang Indonesia. Ia memberi peringatan serius bahwa kondisi ini memicu krisis kesehatan mental dan berdampak pada pembangunan SDM Indonesia (kemkes.go.id, 26/11/2025). Data Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS), mencatat satu dari tiga remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental sementara satu dari dua puluh remaja Indonesia memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Angka ini setara dengan 15,5 juta dan 2,45 juta.
Di hadapan realitas ini, generasi seperti apa yang tengah dibentuk era digital? Bagaimana dan ke mana arah aktivisme digital yang digerakkan oleh generasi dengan daya tahan mental yang lemah?
Hegemoni Digital Kapitalisme-Sekulerisme
Penting untuk disadari bahwa dunia digital tidak netral. Ia dibangun di atas fondasi kapitalisme-sekuler. Tatanan kapitalisme memang sempat menunjukkan tanda-tanda kebangkrutannya pada 2020-2021 masa COVID-19 dengan runtuhnya pasar saham. Slavoj Žižek bahkan menyebut dalam bukunya Pandemic!: COVID-19 Shakes the World (2020), pandemi adalah awal dari akhir kapitalisme neoliberal.
Nyatanya kapitalisme tidak mati, ia justru bangkit dengan wajah baru: kapitalisme platform. Yaitu perusahaan raksasa teknologi (Big-Tech) menguasai infrastruktur digital yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Data, algoritma, dan atensi manusia dijadikan sumber keuntungan utama.
Dominasi ini melahirkan hegemoni digital. Platform tidak hanya menyediakan layanan, tetapi memproduksi budaya dan membentuk kesadaran. Algoritma menentukan apa yang layak dilihat, dibicarakan, dan dipercaya. Kontrol sosial dijalankan secara halus melalui kenyamanan, bukan paksaan.
Sebagian besar platform digital lahir dari Barat dengan nilai sekuler sebagai fondasi. Agama diposisikan sebagai urusan privat, sementara kebebasan individual dan gaya hidup liberal dinormalisasi. Konten keagamaan yang bersifat ritual dan motivasional diberi ruang, tetapi pemikiran Islam yang ideologis dan kritis kerap dibatasi. Istilah, wacana, dan diskursus politik Islam sering kali diawasi ketat atau dipinggirkan secara senyap.
Algoritma bekerja bukan untuk mencerdaskan, tetapi untuk mempertahankan atensi. Konten hiburan, sensasi, dan emosi lebih diprioritaskan karena menguntungkan secara bisnis. Akibatnya, pandangan hidup generasi muda dibentuk oleh apa yang viral, bukan apa yang benar. Tanpa disadari, algoritma menjadi “guru nilai” baru yang membentuk moral dan cara pandang.
Skemanya sederhana: semakin lama kita online, semakin banyak iklan yang ditampilkan, dan semakin besar keuntungan platform. Bersamaan dengan itu, paparan konten sekuler yang merusak kian masif dikonsumsi. Situasi ini sangat menguntungkan, baik secara ekonomi maupun ideologis bagi kapitalisme-sekuler.
Jebakan Slacktivism
Dalam konteks ini, aktivisme digital pemuda Muslim patut dikritisi. Gelombang solidaritas di media sosial sering tampak masif, tetapi rapuh. Banyak gerakan lahir bukan dari kesadaran ideologis, melainkan dorongan viralitas. Jangan sampai aktivisme pemuda muslim terjebak pada slacktivism. Slacktivism adalah bentuk “aktivisme malas”. Seseorang terlihat peduli dan aktif di media sosial, tetapi keterlibatannya berhenti pada aksi simbolik, tanpa upaya nyata untuk mendorong perubahan. Contohnya, hanya membagikan poster perjuangan, mengganti foto profil dengan simbol solidaritas, meramaikan tagar, memberi like atau komentar semangat emosional. Namun alpa dalam perjuangan di dunia nyata.
Semua itu terlihat aktif, tetapi sering tidak berlanjut pada tindakan nyata atau perjuangan jangka panjang. Partisipasi simbolik di ruang digital dianggap cukup sebagai bentuk perjuangan. Padahal, aktivitas ini tetap menguntungkan platform. Kritik berubah menjadi komoditas. Perlawanan direduksi menjadi konten. Energi pemuda habis dalam ekspresi emosional tanpa arah perubahan yang jelas.
Akibatnya, banyak pemuda marah pada gejala, tetapi gagal membaca sistem. Mereka peduli pada ketidakadilan, tetapi tidak menantang paradigma yang melahirkannya. Aktivisme pun mudah dibajak oleh agenda liberal, demokrasi prosedural, atau kepentingan politik pragmatis. Semangat besar pemuda justru berputar di dalam lingkaran kapitalisme yang sama.
Aktivis pemuda muslim juga harus menyadari, bahwa algoritma platform tidak didesain untuk memenangkan opini Islam. Selama opini-opini Islam tidak mengancam struktur ideologis platform, aktivisme dibiarkan tumbuh. Namun ketika menyentuh akar persoalan sistemik, jangkauannya dipersempit.
Dampaknya, generasi muda kerap merasa telah berjuang, meski kritiknya belum menyentuh akar persoalan. Sistem sekuler-kapitalistik tetap bertahan, sementara viralitas disalahartikan sebagai perubahan.
Urgensi Ideologisasi Islam
Di sinilah urgensi ideologisasi Islam menjadi nyata. Ideologisasi bukan sekadar penguatan identitas simbolik atau motivasi spiritual. Ia adalah proses menata ulang cara berpikir, menilai, dan bergerak berdasarkan akidah Islam. Islam harus kembali diposisikan sebagai ideologi yang menyeluruh, bukan sekadar agama ritual.
Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam Nizham al-Islam menjelaskan, “Kita harus mengambil Islam secara sempurna, baik di akidah maupun peraturannya; serta hendaknya kita mengemban qiyadah fikriyyah (kepemimpinan berpikir Islam pada saat kita mengemban dakwah Islam. Sesungguhnya jalan kebangkitan kita hanya satu, yaitu melanjutkan kembali kehidupan Islam. Tidak ada jalan lain untuk melanjutkan kehidupan Islam itu kecuali dengan tegaknya Daulah Islam. Dan hal itu tidak dapat diraih kecuali kita mengambil Islam secara total, yaitu mengambil Islam sebagai akidah yang mampu memecahkan masalah utama (al-uqdatul kubra) manusia, yang di atasnya dibangun pandangan hidup; juga mengambilnya sebagai peraturan yang terpancar dari akidah Islam.”
Beliau juga menyatakan bahwa satu-satunya jalan untuk menghasilkan kebangkitan adalah dengan mengemban qiyadah fikriyyah (kepemimpinan berpikir) Islam kepada kaum muslim untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam, kemudian menyebarluaskannya kepada umat manusia melalui Daulah Islam.
Allah Taala berfirman,
إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
“Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan-Nya.”(QS Ali Imran: 19).
Dengan kerangka ideologis Islam, generasi muda mampu membaca realitas secara jernih. Krisis umat dipahami sebagai akibat penerapan sistem sekuler-kapitalistik, bukan sekadar kesalahan teknis atau moral individu. Perjuangan tidak berhenti pada aktivisme moral, tetapi diarahkan pada perubahan sistemik.
Ideologisasi juga membentengi generasi muda dari manipulasi algoritma. Mereka tidak lagi larut sebagai konsumen konten, tetapi tampil sebagai subjek perubahan. Dunia digital dimanfaatkan sebagai medan dakwah dan pembentukan opini Islam, bukan sekadar ruang ekspresi emosional.
Karena itu, generasi muda harus memahami makna dan arah perubahan yang hakiki dalam Islam. Dan mengambil peran aktif dalam memperjuangkannya. Teknologi harus dipandang sebagai sebuah madaniyah (produk kemajuan ilmu) yang bersifat alat bukan tujuan. Dan memahami sepenuhnya bahwa dunia digital tengah di hegemoni Barat-kapitalis. Sudah semestinya teknologi difungsikan sebagai sarana dakwah dan perjuangan, bukan justru menjauhkan dari amanah perubahan.
Dengan demikian, pembinaan Islam ideologis bagi generasi muda adalah sebuah kebutuhan, bukan pilihan. Peran mereka sebagai hamba Allah di muka bumi adalah menjadi pelopor perubahan menuju peradaban Islam. Wallahu ‘alam bisshowab.